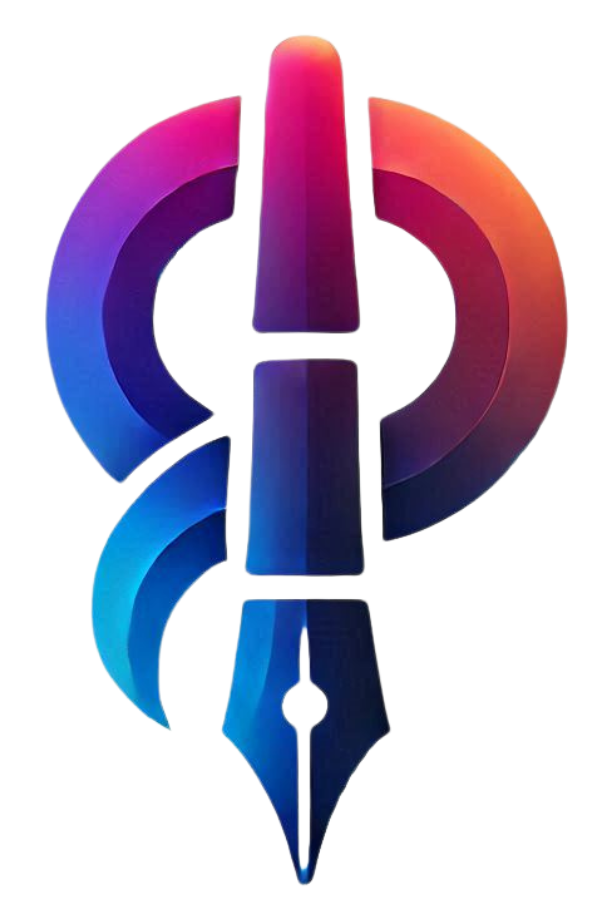Table of Contents
Lagi scroll medsos, nonton debat atau lihat konten, lalu kamu merasa argumen orang itu “kayak ada yang janggal”, tapi susah dijelasin salahnya di mana?
Nah, kemungkinan besar itu karena logical fallacy alias kesalahan logika.
Apa itu Logical Fallacy? Apa sama dengan Bias Kognitif?
Jadi sebenarnya, apa itu logical fallacy? Apa sama dengan bias kognitif?
Gampangnya, logical fallacy adalah kesalahan dalam menyusun argumen. Biasanya muncul di debat, diskusi, atau saat seseorang lagi berusaha meyakinkan orang lain.
Kesalahan ini bisa saja disengaja (untuk manipulasi pikiran lawan) atau nggak sengaja karena keterbatasan skill dan pengetahuan.
Sedangkan, bias kognitif adalah kesalahan dalam cara otak memproses info.
Bias kognitif lebih ke shortcut otak biar dapat kesimpulan cepat. Ini nggak muncul dengan sengaja, melainkan karena faktor pengalaman, emosi, atau kebiasaan.
Nah, sampai di sini mulai kelihatan bedanya, kan, apa itu Logical Fallacy? Logical fallacy adalah logika argumen yang salah. Sedangkan bias masih berupa pola pikir di dalam otak.
Kenapa Kita Harus Tahu Apa Itu Logical Fallacy?
Karena makin hari, makin banyak logical fallacy yang bertebaran di konten, debat, bahkan berita. Kalau nggak hati-hati, kita bisa gampang banget kecele, misalnya ikut pendapat influencer tanpa arah lantas terjebak hoax.
Dengan mengerti logical fallacy, kita bisa:
- Lebih kritis waktu baca/lihat info
- Nggak gampang termakan argumen menyesatkan
- Makin jago kalau debat (nggak asal baper)
Terus, Apa Saja Jenis-Jenis Logical Fallacy yang sering terjadi?
Ini adalah beberapa contoh Logical Fallacy yang bakal sering kalian jumpai :
1. Ad Hominem (Logical Fallacy yang nyerang orangnya, bukan argumennya)
Ad hominem adalah logical fallacy di mana seseorang menyerang pribadi lawan bicara, bukan isi argumennya. Jadi alih-alih membahas apa yang dikatakan, fokusnya malah ke siapa yang bicara.
Tujuannya untuk :
- menjatuhkan kredibilitas lawan,
- membuat argumennya terlihat lemah, atau
- membuat lawan kehilangan muka.
Padahal, meski orangnya punya kelemahan, argumennya bisa tetap valid.
Jenis-Jenis Ad Hominem :
- Abusive Ad Hominem (menyerang sosok orangnya langsung). Contoh : “Dia ngomong soal politik? Ah, dia kan bodoh.”
- Circumstantial Ad Hominem (nyerang keadaan/posisi). Contoh : “Kamu bilang jangan investasi di kripto, ya wajar, kamu kan kerja di bank.”
- Tu Quoque (Kamu juga gitu / Hipokrisi). Contoh : “Kamu bilang nggak berhijab dosa? Emangnya kamu nggak punya dosa?”
- Guilt by Association (menyerang hubungan seseorang dengan orang lain) Contoh : “Dia kritik pemerintah terus, itu kan karena dia anak abah.”
Kenapa Ad Hominem Termasuk Logical Fallacy?
Karena kondisi personal nggak ada hubungannya dengan validitas argumen. Kalau narapidana bilang mencuri itu perbuatan buruk, ucapan itu tetap benar meskipun dia penjahat.
Kalau dokter yang merokok bilang bahwa merokok merusak paru-paru, faktanya tetap valid meskipun dia munafik.
2. Strawman (Logical Fallacy dengan bikin “boneka jerami” biar gampang dibantah)

Strawman fallacy adalah logical fallacy ketika seseorang menyalah-artikan sebuah argumen, menyederhanakan atau menarik ke titik ekstrim, lalu menyerang versi yang salah itu, bukan argumen yang awal.
Pelaku strawman tidak membantah isi argumen asli, melainkan membuat “boneka jerami” (strawman) lalu menghancurkan boneka itu supaya terlihat menang debat.
Polanya :
- Lawan bicara mengemukakan argumen A.
- Si penyerang menyederhanakan/mengubah argumen A menjadi versi lemah yang lebih mudah diserang (B)
- Lalu dia menyerang B, seolah-olah itu argumen aslinya
Jenis-jenis Strawman Fallacy :
- Exaggeration (melebih-lebihkan) yaitu menarik argumen lawan ke titik ekstrem. Contoh: “Kamu bilang macet bisa diatasi dengan memperbanyak dan memperbaiki transportasi umum? Jadi memiliki kendaraan pribadi dan menggunakannya untuk bepergian adalah sebuah kesalahan dong? Apa salahnya orang mau punya kendaraan pribadi dan bepergian dengan mobil favoritnya?”
- Oversimplification (menyederhanakan secara berlebihan). Contoh: “Dia bilang diet penting buat kesehatan. Padahal olahraga juga terbukti menyehatkan badan lho.” (Padahal diet bikin sehat bukan berarti diet dalah satu-satunya cara biar badan sehat)
- Distortion (memelintir makna). Contoh : “Kamu ajak masyarakat demo dengan damai? Kamu buzzer yang ingin masyarakat bungkam ya?”
3. False Dilemma (Logical fallacy dengan menciptakan dilema palsu)
False dilemma adalah logical fallacy ketika seseorang menyajikan dua pilihan seolah-olah hanya ada dua opsi itu saja yang tersedia, padahal kenyataannya masih ada alternatif lain.
Jadi seakan-akan situasinya hitam-putih, “kalau bukan A, ya pasti B,” padahal dunia seringkali lebih kompleks.
Jenis-jenis False Dilemma :
- With us or against us. Contoh: “Kalau kamu anti patriarki, berarti kamu aktivis feminis.”
- Excluding the middle, alias mengabaikan adanya solusi kompromi. Contoh: “Kamu harus pilih jadi ibu rumah tangga dan merawat anak-anakmu dengan baik atau punya karir dan anak-anakmu jadi terlantar kurang kasih sayang.”
4. Circular Reasoning (Logical fallacy yang argumennya muter-muter doang)
Circular reasoning adalah logical fallacy ketika kesimpulan yang mau dibuktikan justru dipakai sebagai premis awal. Jadi argumennya muter-muter tanpa bukti tambahan.
Contoh :
A : Apa buktinya bahwa kitab itu benar dan berasal dari Tuhan?
B : Karena tertulis di dalam kitab ini bahwa kitab ini pasti benar dan berasal dari Tuhan
5. Slippery Slope (kasih efek domino yang kejauhan)

Slippery slope adalah logical fallacy ketika seseorang bilang kalau sebuah tindakan kecil bakal otomatis bikin rangkaian kejadian ekstrem yang nggak terkendali.
Contoh :
“Kalau anak dikasih gadget sekarang, besok kecanduan, terus nggak mau sekolah, akhirnya jadi pengangguran.”
“Kalau tiap hari masakan dikasih micin, otak kita jadi bodoh, lama-lama jadi nggak kritis dan negara nggak maju-maju.”
Kenapa slippery slope sering dipakai?
Jawabannya sangat jelas. Slippery slope memanfaatkan rasa takut seseorang. Orang gampang takut pada efek domino.
Dan walaupun kelihatan logis sekilas, pada slippery slope, sebab akibat terlalu jauh dan seringkali diambil tanpa konteks juga mengabaikan fakta ada tahapan-tahapan tertentu sebelum titik ekstrim terjadi.
Cara ini cocok buat memanipulasi lawan bicara. Biasanya dipakai di politik, iklan, bahkan obrolan sehari-hari. Ini adalah teknik manipulasi yang sering dipakai agar orang-orang secara berlebihan menjadi anti sufor, anti vaksin, anti UPF sampai anti pemerintahan.
6. Appeal to Authority (Logical fallacy berupa kepercayaan buta kepada orang yang punya pengaruh)
Appeal to authority adalah logical fallacy ketika orang menganggap suatu pernyataan pasti benar hanya karena diucapkan oleh figur otoritas, pakar, atau orang terkenal.
Masalahnya bukan pada pakar/otoritasnya, tapi pada cara orang berhenti berpikir kritis dan langsung percaya tanpa bukti. Hanya karena yang mengucapkan punya nama besar, dianggap apa yang dia katakan pasti benar, logika lain diabaikan.
Contoh :
“Mama udah hidup lebih lama daripada kamu, jadi pasti mama benar.”
“Penulis kondang itu aja bilang tindakan ini bukan plagiarisme kok.”
“Yang mimpin sholawat sambil joget-joget tuh anak kiyai lho.”
Appeal to authority cukup berbahaya. Ini bisa bikin kita terjebak dogma dan menumpulkan critical thinking.
7. Bandwagon (Logical fallacy yang sekadar ikut-ikutan)
Bandwagon fallacy adalah logical fallacy ketika orang menganggap sesuatu itu benar atau baik hanya karena banyak orang percaya atau melakukan hal itu.
Bahasa gampangnya: “Kalau semua orang ikut, berarti itu pasti benar.”
Contoh :
“Dari dulu juga kalau orang meninggal tuh ya keluarganya tahlilan.”
“Hampir semua teman nyontek pas ujian, berarti nggak masalah dong kalau aku juga nyontek.”
8. False Equivalence (Logical fallacy yang kasih perbandingan nggak setara)
False equivalence adalah logical fallacy ketika dua hal dibandingkan seolah-olah setara, padahal sebenarnya konteks, sifat, atau dampaknya berbeda jauh. Jadi, seseorang membuat analogi atau perbandingan yang kelihatan adil di permukaan, tapi kalau dikaji lebih dalam, justru menyesatkan.
Contoh :
“Rokok mau dibatasi karena membahayakan kesehatan? Kalau begitu, gula juga harus dibatasi peredarannya dong karena lebih berbahaya. Bahkan lebih banyak orang mati karena gula daripada rokok. Kenapa gula nggak dilarang juga?”
Apa Bias Kognitif Menyebabkan Kita Terjebak dalam Logical Falacy?
Ya, sangat bisa. Bias kognitif bisa menyebabkan kita terjebak dalam logical fallacy. Ketika bias itu terbawa ke cara kita ngomong atau membangun argumen, hasilnya jadi logical fallacy.
Kalau bias itu ibarat “akar” di dalam pikiran, maka fallacy adalah “buah” yang keluar pas kita ngomong. Jadi wajar banget kalau dua hal ini saling nyambung.
Contohnya gini : kita punya bandwagon bias—cenderung percaya sama sesuatu cuma karena banyak orang juga percaya. Pas dibawa ke argumen, jadilah bandwagon fallacy.
Atau saat kita terjebak confirmation bias, otak kita otomatis mencari bukti yang sejalan sama pendapat sendiri.
Yang membuat semakin tricky adalah bias kognitif itu sendiri seringnya nggak terasa. Dan logical fallacy yang lahir dari bias itu terdengar meyakinkan, bahkan bisa bikin orang lain ikut percaya.
Lingkungan juga seringkali malah menjadi pendukung, misalnya timeline medsos, tren, atau circle pertemanan, semua itu bisa makin menguatkan bias sampai kita yakin banget kalau logika kita flawless.
Padahal, di situlah jebakannya. Tanpa sadar kita udah mencampur aduk antara apa yang otak “ingin” percaya dengan apa yang benar-benar logis. Karena itu, kalau mau debat lebih sehat, kita harus berani rem dan slowdown dulu. Tanyakan pada diri sendiri: “Keyakinanku ini karena logika, atau cuma karena biasku aja?”
Kalau nggak hati-hati, bias kognitif bisa jadi pintu masuk ke segala macam logical fallacy. Begitu kita ngerti apa itu logical fallacy, bias kognitif dan hubungan antara keduanya, kita bisa lebih waspada, baik pas bikin argumen sendiri maupun saat mendengarkan orang lain.
Intinya, jangan gampang percaya sama hal yang terdengar logis di permukaan. Kadang, itu cuma bias yang disulap jadi fallacy.
Nah, gimana caranya agar bias kita nggak menyebabkan fallacy?
Sebenarnya, hampir semua orang rentan banget terjebak dalam logical fallacy karena punya bias kognitif masing-masing.
Cara paling penting agar bias nggak bikin kita jatuh ke dalam logical fallacy adalah dengan belajar pause dulu sebelum bicara. Bayangkan ada tombol jeda.
Saat ada argumen memanas, bias kita biasanya langsung lompat ke mode defensif : “Ah, pasti dia salah. Aku harus balas.”
Padahal, justru di momen itu kita harus nanya ke diri sendiri : “Eh, aku lagi menyerang argumen dia, atau malah nyerang orangnya? Aku beneran ngebandingin hal yang setara, atau cuma cari contoh asal-asalan buat kasih lawan?”
Bukan berarti kita harus jadi robot yang selalu logis 100%. Tapi dengan sadar dengan bias kita sendiri, kita bisa lebih pelan-pelan menilai argumen. Kadang cukup dengan sadar dan menerima : “Oke, aku mungkin condong mikir seperti ini karena pengalaman pribadi, tapi coba aku cek lagi deh logikanya,” itu sudah langkah besar buat mencegah fallacy.
Terus nih, gimana cara tahu argumen lawan bicara mengandung logical fallacy dan harus gimana meresponnya?
Biasanya, cara paling gampang tahu argumen lawan itu jatuh ke logical fallacy adalah dengan sadar bahwa ada ada “loncatan logika” yang bikin kita berpikir, “loh, kok tiba-tiba nyambungnya ke situ?”
Misalnya, kamu lagi ngomongin soal kebijakan kesehatan, eh lawan bicara malah bilang, “Tapi kan kamu juga dulu pernah sakit karena kebanyakan begadang, jadi nggak usah sok tahu soal kesehatan.” Nah, kalau kamu ngerasa topiknya jadi belok ke personal, itu tanda besar ada fallacy ad hominem di situ.
Atau contoh lain, saat ada yang bilang, “Kalau cewek mau setara, berarti boleh dong cowok mukul cewek?” Kalau kamu merasakan ada yang “nggak nyambung” antara konsep kesetaraan dengan kekerasan, berarti argumennya kemungkinan strawman atau false equivalence.
Nah, begitu kita sadar ada fallacy, pertanyaan berikutnya adalah harus gimana responnya? Ada dua pilihan, tergantung situasi.
Saat lagi debat serius, kamu bisa call out langsung dengan santai bahwa lawan bicaramu jatuh ke dalam logical fallacy.
Jadi lawan bicara dipaksa balik ke jalur logis. Tapi kalau suasana lagi panas atau debatnya nggak sehat, kadang lebih bijak buat nggak meladeni. Karena orang yang sudah terjebak logical fallacy sering nggak nyadar, dan kalau dipaksa, malah makin ngotot.
Respon paling elegan sebenarnya bukan sekadar bilang, “Itu fallacy!” (karena bisa kedengeran sok pintar), tapi dengan kasih klarifikasi pelan-pelan.
Misalnya: “Nggak bisa dong bandingin gula sama rokok. Rokok itu berbahaya meski dalam jumlah kecil, sementara gula baru bahaya kalau berlebihan. Selain itu, secara fungsional juga sangat berbeda.”
Jadi kamu bukan cuma nuduh lawan jatuh ke fallacy, tapi sekalian kasih jalan keluar biar argumen balik ke arah yang sehat.
Peran Literasi di mana nih untuk Mencegah Logical Fallacy?
Peran literasi sangat besar supaya kita nggak gampang jatuh ke logical fallacy. Literasi bukan cuma soal bisa baca-tulis, tapi juga kemampuan memahami bacaan itu dan melek informasi, mengerti konteks, bisa bedakan fakta vs opini, dan bisa menangkap alur logika dari sebuah argumen.
Bayangkan, kalau kita minim literasi, terlalu mudah buat kebawa emosi atau terjebak kata-kata manis. Misalnya ada politisi bilang, “Kalau saya nggak dipilih, negara ini akan hancur.”
Orang yang literasinya rendah mungkin langsung percaya, karena kalimatnya terdengar meyakinkan. Padahal itu contoh klasik false dilemma, seolah-olah cuma ada dua pilihan, padahal realitanya jauh lebih kompleks. Dengan literasi yang baik, kita bisa mikir, “Eh, bener nggak sih? Apa iya cuma ada dua opsi? Data apa yang mendukung klaim itu?”
Literasi juga bikin kita sadar bahwa banyak logical fallacy sengaja dipakai untuk memanipulasi. Contoh dalam perdebatan gender: “Kalau perempuan minta kesetaraan, kenapa nggak mau jadi kuli?”
Orang yang terbiasa baca isu gender dengan literasi kritis akan tahu ini false equivalence sekaligus strawman, karena kesetaraan hak bukan berarti harus mau mengerjakan semua pekerjaan laki-laki termasuk kuli tapi ketika perempuan mau jadi kuli, mereka punya kesempatan asal punya kemampuan. Toh juga nggak semua laki-laki mampu dan mau jadi kuli.
Singkatnya, literasi itu kayak vaksin buat otak. Dengan rajin baca, kritis pada sumber dan terbiasa menimbang logika, kita jadi lebih tahan terhadap argumen-argumen menyesatkan dan hoaks.
Terakhir, logical fallacy yang aku terangkan di sini belum semua. Kalau kamu mau baca macam-macam logical fallacy yang lain dengan lebih lengkap dan sederhana, kamu bisa baca di buku “Logical Fallacy” karangan Muhammad Nuruddin ini