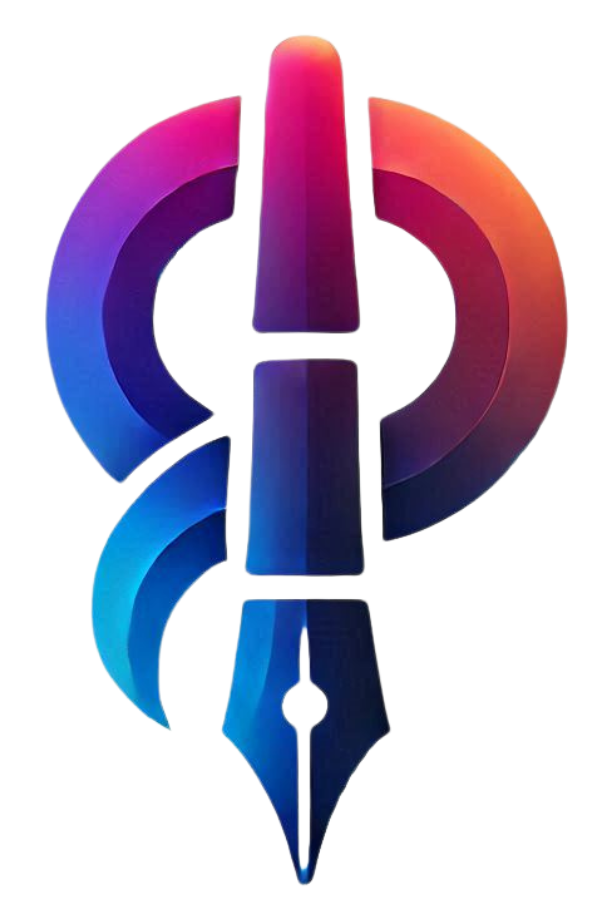Table of Contents
Pernah nggak, kamu merasa udah mikir matang-matang, tapi akhirnya tetap salah langkah? Misalnya, yakin banget barang diskon di mall adalah kesempatan langka lalu kamu membelinya, eh begitu sampai rumah baru sadar kalau kamu nggak terlalu butuh.
Atau yang paling sering terjadi belakangan adalah percaya sama kabar heboh di media sosial, padahal pada akhirnya ketahuan bahwa itu hoaks.
Sering kali, biang keladinya adalah bias kognitif, cara kerja otak yang diam-diam “menipu” kita dengan logika semu.
Artikel ini akan bahas apa itu bias kognitif, macam-macam yang paling sering kita alami, dan gimana cara mengenalinya supaya kita nggak gampang kejebak.
Apa Itu Bias Kognitif?
Bayangkan otak kita adalah autopilot di pesawat. Autopilot dibuat supaya pilot nggak kelelahan harus mengendalikan semua tombol dan tuas secara manual sepanjang penerbangan.
Sistem ini bisa membaca pola, arah angin, dan jalur terbang dengan cepat. Dengan begitu, pesawat bisa melaju mulus tanpa pilot harus repot setiap detik.
Nah, otak juga begitu. Setiap hari kita dibombardir miliaran informasi berupa suara, gambar, percakapan, berita, emosi, iklan, sampai notifikasi HP. Kalau semua diproses detail satu-satu, kepala kita bisa “overheat”.
Karena itu, otak punya “mekanisme hemat energi” berupa jalan pintas berpikir yang disebut heuristik.
Heuristik ini sebenarnya berguna. Misalnya, kalau lihat asap kita langsung mengaitkannya dengan api tanpa harus menganalisis panjang lebar. Cepat dan efisien. Tapi, mekanisme yang sama juga bisa keliru.
Saat otak terlalu mengandalkan heuristik, lahirlah bias kognitif yaitu kesalahan pola pikir yang bikin kita salah menilai situasi atau mengambil keputusan yang nggak rasional.
Bias Kognitif Apa Saja yang Paling Sering Menjebak Kita?
1. Confirmation Bias
Confirmation bias adalah kecenderungan otak kita untuk lebih percaya, mencari, atau mengingat informasi yang mendukung apa yang sudah kita yakin, sementara informasi yang berlawanan sering diabaikan atau ditolak.
Secara psikologi, ini terjadi karena otak kita nggak suka dengan “ketidaknyamanan”, bahasa kerennya cognitive dissonance. Jadi kalau ada fakta yang bertentangan dengan keyakinan kita, otak otomatis berusaha menyingkirkannya supaya kita tetap merasa “benar”.
Contoh nyatanya :
Kalau seseorang sudah punya kebencian pada pemerintah, setiap berita buruk tentang pemerintah terasa masuk akal dan gampang dipercaya, bahkan tanpa dicek kebenarannya. Sebaliknya, berita baik yang menunjukkan keberhasilan pemerintah sering dianggap palsu, manipulasi, atau langsung diabaikan.
Sama halnya dengan fans olahraga. Kalau tim kesayangan kalah, orang bisa bilang “wasitnya curang” atau “lawannya main kasar.” Tapi kalau menang, langsung yakin itu murni karena timnya hebat.
2. Anchoring Bias
Anchoring bias adalah kecenderungan kita terlalu terpengaruh oleh informasi pertama (atau angka awal) yang kita dapat, lalu menjadikannya “jangkar” dalam membuat keputusan, meskipun informasi itu belum tentu akurat.
Secara psikologi, otak kita suka pakai heuristik angka awal sebagai patokan supaya lebih gampang menghitung dan menilai. Masalahnya, “angka jangkar” ini sering bikin penilaian kita melenceng.
Contoh nyatanya :
Saat tawar-menawar harga, penjual bilang harga motor Rp 30 juta. Kamu nggak tahu kalau harga pasarnya cuma Rp 25 Juta.
Tapi karena angka pertama yang masuk ke kepalamu adalah Rp 30 Juta, saat harga diturunkan jadi Rp 27 Juta, kamu jadi merasa harga motornya murah, padahal tetap kemahalan.
3. Availability Bias

Availability bias adalah kecenderungan kita menilai sesuatu lebih sering terjadi atau lebih penting hanya karena contoh atau ingatannya gampang muncul di kepala.
Secara psikologi, ini terjadi karena otak kita lebih suka pakai memori yang mudah diakses (available) daripada repot-repot mencari data lengkap. Kalau ada hal yang heboh, emosional, atau baru saja terjadi, otak otomatis menganggap itu lebih dominan daripada kenyataannya.
Contoh nyatanya :
Setelah lihat berita kecelakaan pesawat di TV, banyak orang jadi parno naik pesawat. Padahal secara statistik, naik pesawat jauh lebih aman dibanding naik motor. Tapi karena gambaran kecelakaan itu jelas dan gampang diingat, otak langsung menganggapnya lebih berbahaya.
Contoh lainnya, kalau ada berita perampokan viral di medsos, kita jadi merasa kota kita makin nggak aman. Padahal angka kriminalitas bisa saja sebenarnya justru turun.
4. Halo Effect
Halo effect adalah bias kognitif ketika satu kesan positif (atau negatif) tentang seseorang atau sesuatu membuat kita menilai semua aspek lainnya ikut positif (atau negatif), padahal belum tentu benar.
Secara psikologi, ini terjadi karena otak kita suka menyederhanakan penilaian. Kalau sudah menemukan satu kualitas menonjol, otak langsung “mengisi sendiri” bagian lain dengan asumsi serupa.
Misalnya ada seorang influencer yang viral karena berani menantang anggota DPR yang sedang blunder dalam debat. Aksinya bikin kita kagum, keren banget, pintar, opini dia benar dan semua yang dia lakukan itu demi negara.
Padahal, kenyataannya belum tentu begitu. Keberanian dia di satu momen memang nyata, tapi itu nggak otomatis berarti semua opini, produk endorse, atau sikapnya di bidang lain selalu benar dan layak diikuti.
Itulah jebakan Halo Effect. Satu cahaya terang (keberanian dia debat) bikin kita menilai seluruh bagian dirinya ikut bersinar.
5. Bandwagon Effect
Bandwagon effect adalah kecenderungan kita untuk ikut-ikutan percaya atau melakukan sesuatu hanya karena banyak orang lain juga melakukannya. Dalam psikologi, otak kita punya dorongan sosial bahwa saat mayoritas melakukan hal tertentu, itu dianggap aman, benar, atau layak diikuti.
Contoh nyatanya :
Kalau kamu lagi jalan di tengah keramaian, lalu tiba-tiba semua orang berteriak dan lari ke satu arah, kamu akan spontan ikut lari ke arah itu tanpa tahu alasannya terlebih dahulu.
Salah satu jenis emosi yang jadi bahan bakar untuk “mempertebal” bandwagon effect adalah FOMO (Fear Of Missing Out) yaitu rasa takut ketinggalan momen atau tren. Misalnya : Saat tiba-tiba semua orang pakai aplikasi baru, kamu juga buru-buru download meski belum paham fungsinya.
6. Sunk Cost Fallacy
Sunk cost fallacy adalah kecenderungan kita untuk terus mempertahankan sesuatu hanya karena sudah terlanjur mengeluarkan banyak waktu, tenaga, atau uang untuknya padahal sebenarnya sudah jelas itu merugikan.
Secara rasional, keputusan seharusnya diambil berdasarkan apa yang terbaik ke depan, bukan berapa banyak yang sudah kita habiskan di masa lalu. Tapi otak kita sering menolak ide itu. “Sayang banget kalau berhenti sekarang, kan udah keluar banyak modal/tenaga.”
Contoh nyatanya :
Kamu sudah menikah dengan pasanganmu selama tujuh tahun. Dia ketahuan selingkuh dan hubungan kalian semakin memburuk, kamu jelas-jelas nggak bahagia. Tapi kamu masih bertahan karena mikir, “Sayang banget kalau cerai, udah sejauh ini, udah terlalu banyak yang kami lalui bersama.”
7. In-group Bias
In-group bias adalah kecenderungan kita untuk lebih membela, memihak, atau melihat positif kelompok kita sendiri, sambil meremehkan kritik atau sisi negatif dari kelompok lain.
Contoh Nyatanya :
Aliran agama A menganggap ajaran kelompoknya yang paling benar sedangkan yang lain salah. Ini juga berlaku dalam kelompok yang satu profesi. Misalnya, seorang guru yang jujur tidak percaya saat ada informasi kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok guru lain.
8. Overgeneralization Bias

Overgeneralization bias terjadi ketika kita menarik kesimpulan terlalu luas dari pengalaman sempit atau bukti kecil. Sederhananya, satu-dua kejadian langsung dianggap mewakili semua hal.
Contoh nyatanya :
Kamu dua kali putus dengan mantan cowok karena diselingkuhi lalu kamu berpikir berarti semua cowok itu tukang selingkuh
9. Self-Serving Bias
Self-serving bias adalah kecenderungan kita untuk mengklaim keberhasilan karena diri kita hebat, tapi kalau gagal, disalahkan ke faktor luar.
Bias ini muncul karena otak kita butuh menjaga harga diri tetap tinggi. Jadi, logika sering dikorbankan demi bikin diri merasa lebih baik.
Contoh nyatanya :
Jika saat ujian dapat nilai bagus, kamu merasa itu karena kamu rajin belajar. Tapi saat dapat nilai jelek kamu berpikir itu karena soalnya terlalu susah, dosennya nggak fair atau sengaja mempersulit.
Gimana Cara Mengenali Bias dan Mengurangi Efeknya?
Kuncinya : tahan dulu sebelum yakin
- Kalau terlalu percaya diri, coba tanyakan pada diri sendiri : “Apa ada info yang bertentangan dengan keyakinanku ini?”
- Kalau lagi dikuasai emosi (marah, senang, takut), cek lagi : “Keputusanku ini logis atau cuma karena emosi?”
- Kalau lihat barang murah/diskon/promo, tanyakan lagi apa memang benar-benar butuh dan cari tahu harga pasarannya
- Jangan hanya percaya pada satu sumber, biasakan cek sumber lain saat ada berita atau informasi
Penutup
Bias kognitif itu mirip ilusi optik dalam pikiran. Nggak kelihatan, tapi bikin kita salah lihat kenyataan. Bedanya, kalau ilusi optik cuma bikin kita salah lihat gambar, bias kognitif bisa bikin kita salah pilih pasangan, salah investasi, sampai salah langkah hidup.
Makanya, kenali biasmu. Karena sering kali, musuh terbesar kita bukan orang lain tapi otak kita sendiri.
Apa bedanya Bias Kognitif dengan Logical Fallacy? Cek di artikel ini, yuk!
Referensi: